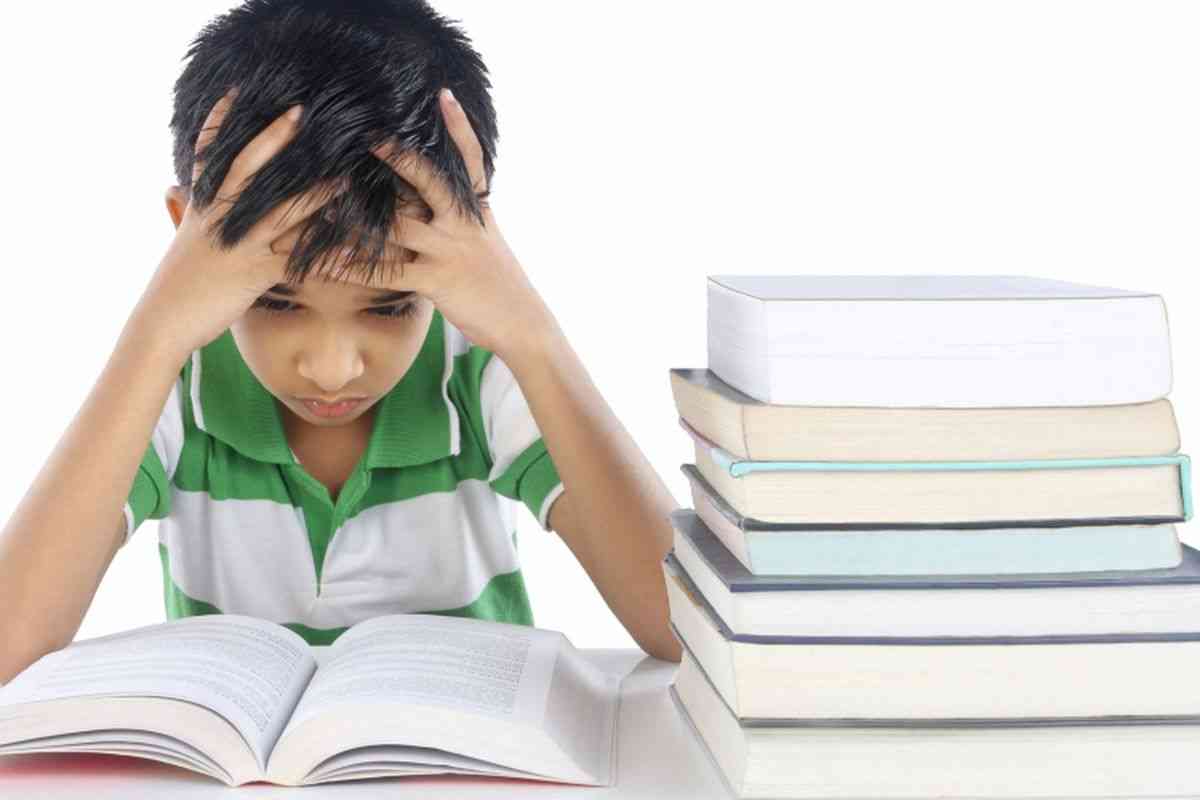Bahasa dan identitas memiliki hubungan erat yang membentuk cara kita dipandang orang lain. Setiap kata, intonasi, hingga pilihan bahasa mencerminkan kepribadian, budaya, bahkan nilai hidup yang kita pegang.
Dalam konteks Indonesia, dengan ratusan bahasa daerah dan ragam dialek, cara bicara seseorang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi cerminan identitas sosial dan budaya.

Bahasa sebagai Cerminan Diri
Pakar linguistik Prof. Dr. Mahsun, M.S. dari Universitas Mataram menegaskan bahwa bahasa mencerminkan pola pikir individu. Orang yang berbicara runtut dan teratur umumnya memiliki logika sistematis. Sebaliknya, mereka yang sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa gaul menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi sosial.
Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Kemendikbudristek RI), bahasa bisa menjadi “cermin sosial” yang memperlihatkan tingkat pendidikan serta latar belakang budaya seseorang.
Identitas Budaya dalam Bahasa
Indonesia tercatat memiliki lebih dari 718 bahasa daerah yang masih bertahan (Kemendikbud, 2024). Setiap bahasa daerah adalah warisan budaya yang sarat makna.
- Bahasa Jawa: memiliki tingkat tutur (ngoko, krama) untuk menunjukkan rasa hormat.
- Bahasa Minangkabau: penuh peribahasa adat yang mencerminkan filosofi hidup.
- Bahasa Papua: lugas dan terbuka, menunjukkan nilai keterusterangan.
Menurut Dr. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, “Bahasa adalah medium paling otentik untuk melihat jati diri bangsa. Hilang bahasa, hilang pula cermin budaya.”

Bahasa Gaul dan Identitas Generasi Muda
Generasi muda di Indonesia kerap menciptakan kosakata baru: anjay, gaskeun, santuy, cuan. Bahasa gaul ini menjadi tanda kebersamaan dan eksistensi di dunia digital.
Namun, Prof. E. Aminudin Aziz, Kepala Badan Bahasa, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kreativitas berbahasa dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika tidak, identitas kebangsaan bisa tergeser oleh tren sesaat.
Cara Bicara sebagai Identitas Sosial
Riset BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) menegaskan bahwa aksen dan dialek dapat membentuk stereotipe sosial. Misalnya:
- Logat Jawa → sering dianggap lemah lembut.
- Logat Batak → identik dengan tegas dan berani.
- Logat Betawi → mencerminkan keterbukaan dan humoris.
Meski begitu, stereotipe ini tidak mutlak. Yang jelas, cara bicara memang menjadi penanda identitas sosial seseorang.
Bahasa dalam Dunia Profesional
Dalam dunia kerja, bahasa dan identitas saling menguatkan. Menurut survei Katadata Insight Center (2024), 70% HRD Indonesia menjadikan kemampuan komunikasi efektif sebagai faktor penentu dalam rekrutmen.
Bahasa formal, jelas, dan terstruktur mencerminkan profesionalitas. Sebaliknya, penggunaan bahasa campuran atau terlalu santai bisa dianggap tidak sesuai dalam situasi resmi.
Bahasa dan Identitas di Era Digital
Media sosial mempertegas hubungan bahasa dan identitas.
- Postingan formal → membangun citra intelektual.
- Chat santai dengan singkatan dan emoji → menunjukkan kepribadian ekspresif.
Selain itu, teknologi AI dan algoritma media sosial menganalisis pola bahasa pengguna untuk menampilkan iklan yang sesuai. Artinya, bahasa yang kita gunakan kini memengaruhi pengalaman digital dan juga persepsi orang lain.
Menjaga Bahasa sebagai Identitas Bangsa
Agar bahasa tetap menjadi identitas bangsa, upaya revitalisasi harus diperkuat. Badan Bahasa Kemendikbud secara aktif melakukan program revitalisasi bahasa daerah di berbagai provinsi.
Peran masyarakat juga penting, seperti:
- Mengajarkan bahasa daerah pada anak sejak dini.
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik.
- Menghargai variasi bahasa gaul sebagai bentuk kreativitas.
Kesimpulan
Bahasa dan identitas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Cara bicara kita mencerminkan kepribadian, budaya, serta nilai sosial. Di era globalisasi dan teknologi, menjaga bahasa berarti menjaga jati diri bangsa.
Seperti kata Ki Hadjar Dewantara, “Bahasa adalah jiwa bangsa. Hilang bahasanya, hilang pula jiwanya.”